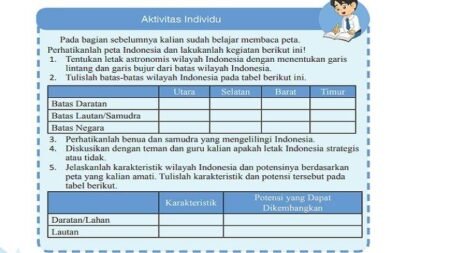Pendekatan Teknokratik dalam Pembangunan Aceh
Pendekapan teknokratik sering dianggap dingin dan elitis. Namun, dalam konteks Aceh, teknokrasi bukanlah sesuatu yang menyingkirkan politik, melainkan justru menyehatkan politik itu sendiri. Politik menentukan arah, sedangkan teknokratik memastikan bahwa arah tersebut ditempuh dengan ilmu, bukan hanya emosi.
Bayangkan bagaimana perubahan bisa terjadi jika setiap keputusan publik didukung oleh riset, data ekonomi, dan proyeksi sosial yang terukur. Dengan pendekatan seperti ini, pembangunan desa akan tampak lebih nyata dan berkelanjutan, karena rencananya disusun berdasarkan data ketahanan pangan dan mitigasi bencana, bukan hanya daftar keinginan politik.
Pendekatan teknokratik memungkinkan Aceh membangun dengan otak yang jernih tanpa kehilangan hati yang “lokal”. Ini adalah cara untuk menjaga keseimbangan antara inovasi dan tradisi.
Mengapa Harus 25 Tahun?
Membangun peradaban butuh satu generasi, bukan sekadar satu periode pemerintahan. Transformasi ekonomi, penguatan pendidikan dan kesehatan, serta penataan tata ruang hanya akan bermakna jika dijalankan secara konsisten lintas pemerintahan. Itulah sebabnya lembaga ini perlu memiliki mandat jangka panjang: untuk menjadi “penjaga arah” pembangunan Aceh.
Dalam jangka 25 tahun, Aceh bisa menyiapkan peta jalan transformasi dari ekonomi ekstraktif menuju ekonomi produktif, dari ketergantungan fiskal menuju kemandirian, dan dari politik simbolik menuju politik berbasis hasil.
Lembaga ini harus berdiri di atas sejumlah prinsip yang tak bisa ditawar: profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas. Ia dikelola oleh orang-orang berintegritas, bukan loyalis politik. Setiap kebijakan yang dikeluarkan harus dapat diuji secara ilmiah dan terbuka untuk publik.
Dengan sistem kerja seperti think-tank resmi yang dilengkapi pusat data dan riset, lembaga ini menjadi otak kolektif bagi pembangunan Aceh—tempat di mana universitas, birokrasi, ulama, dan dunia usaha bertemu untuk menimbang masa depan bersama.
Keuntungan Membangun dengan Pendekatan Teknokratik
Ini bukan lembaga untuk membagi proyek, melainkan untuk menjaga mimpi tetap hidup. Keuntungannya jelas: pembangunan Aceh akan menjadi lebih konsisten, efisien, dan terarah. Program lintas sektor akan selaras, tidak saling tumpang tindih. Hubungan Aceh–Pusat menjadi lebih rasional dan harmonis. Dana publik digunakan dengan perhitungan jangka panjang.
Di atas semua itu, lembaga ini akan melahirkan generasi baru teknokrat lokal—perencana, ekonom, dan insinyur yang berpikir melampaui politik harian. Inilah investasi pengetahuan yang sesungguhnya, membangun manusia yang mampu merancang masa depan, bukan sekadar mengelola masa kini.
Teknokrasi dan Demokrasi
Sebagian mungkin berkata, bukankah teknokrasi berisiko menyingkirkan aspirasi rakyat? Pertanyaan ini sah. Tapi jawabannya sederhana: tidak ada demokrasi yang sehat tanpa rasionalitas. Tanpa lembaga yang menjamin kesinambungan kebijakan, demokrasi hanya akan melahirkan kegaduhan lima tahunan.
Politik tanpa teknokrasi seperti kapal tanpa peta, berlayar tapi tersesat. Itu yang telah terjadi selama 20 tahun terakhir. Hal itu pula yang terjadi di mana-mana—kawasan, negara, yang gagal membangun di seluruh dunia.
Justru dengan lembaga teknokratik, aspirasi rakyat dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang terukur dan berkelanjutan—bukan sekadar janji kampanye yang terlupakan setelah pemilu.
Masalah Aceh Bukan pada Kurangnya Ide, Tetapi pada Hilangnya Kontinuitas
Masalah Aceh bukan pada kurangnya ide, tetapi pada hilangnya kontinuitas. Setiap pemerintahan punya “program unggulan” sendiri, tapi tak ada yang menjaga kesinambungan antarperiode. Kita seperti membangun rumah di atas pasir. Setiap badai politik mengguncangnya, setiap pergantian pemimpin merobohkannya.
Lembaga teknokratik dengan horizon 25 tahun memberi Aceh fondasi baru yang kokoh—fondasi pengetahuan, bukan retorika.
Era Data dan Inovasi
Kita hidup di era di mana data lebih berharga daripada batu bara, dan inovasi lebih bernilai daripada minyak dan gas alam. Tapi banyak daerah, termasuk Aceh, masih memperlakukan ilmu sebagai pelengkap birokrasi, bukan mesin utama pembangunan.
Padahal dunia sedang berubah cepat: digitalisasi, transisi energi, perubahan iklim, globalisasi dan deglobalisasi ekonomi, perubahan geo politik—semua menuntut kesiapan teknologis dan pengetahuan strategis.
Sekarang, Bukan Nanti
Jika Aceh ingin tetap relevan dalam 25 tahun ke depan, ia harus berani menata ulang sistemnya sekarang, bukan nanti. Lembaga teknokratik adalah kendaraan menuju masa depan itu.
Sebagian mungkin bertanya, bukankah ini ambisi besar di tengah birokrasi yang berat? Ya, besar. Tapi setiap lompatan sejarah selalu dimulai dari keberanian berpikir melampaui kebiasaan.
Dulu, ketika Sultan Malik al-Saleh mendirikan Samudera Pasai, atau Ali Mughayatsyah membangun kerajaan Aceh mereka juga melakukan hal yang sama. Mereka menutup lembaran lama, menciptakan sistem baru yang lebih rasional, terbuka, dan berorientasi masa depan.
Kini, lebih dari 6 abad kemudian, Aceh kembali dihadapkan pada pilihan serupa—antara bertahan dalam pola lama, atau menulis babak baru dengan keberanian yang sama.
Mungkin ini saatnya kita bertanya dengan jujur. Maukah kita terus mengulangi pola pembangunan jangka pendek yang meninabobokan, atau berani menyiapkan institusi jangka panjang yang menjamin masa depan?
Maukah kita berhenti membangun proyek, dan mulai membangun peradaban?
Pertanyaan itu bukan untuk birokrat, tetapi untuk seluruh rakyat Aceh yang ingin melihat negerinya berdiri sejajar dengan berbagai kawasan Nusantara maupun dunia.
Karena masa depan tidak dimenangkan oleh yang paling berkuasa, tetapi oleh yang paling terencana.
Dua puluh tahun setelah damai, Aceh membutuhkan satu hal yang lebih berharga daripada dana otsus: visi yang bertahan lebih lama dari jabatan siapa pun.
Lembaga Otoritas Teknokratik Aceh–Pusat bukan sekadar gagasan administratif. Ini adalah pernyataan bahwa Aceh siap naik kelas—dari politik menuju pengetahuan, dari retorika menuju rasionalitas, dan dari sejarah menuju masa depan.