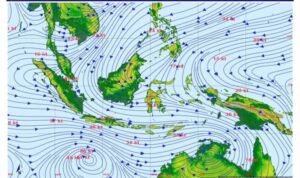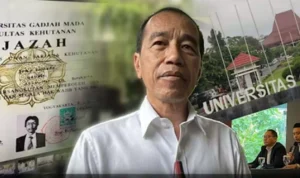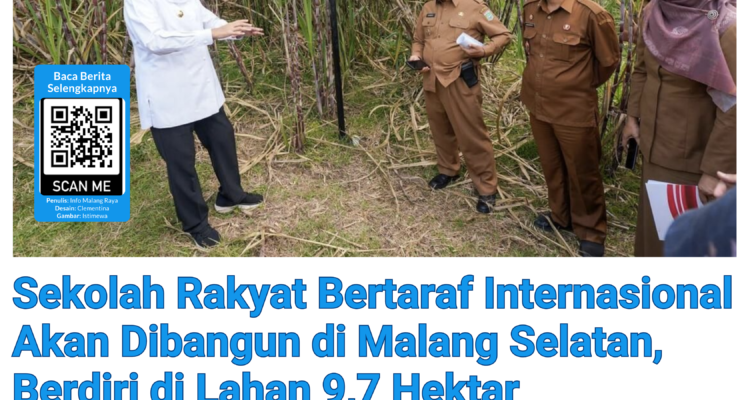Setiap tanggal 1 Mei, dunia memperingati Hari Buruh Internasional—sebuah momentum global untuk mengenang perjuangan kelas pekerja serta menyoroti persoalan kesejahteraan yang masih menjadi pekerjaan rumah hingga kini. Di berbagai negara, termasuk Indonesia, tanggal ini kerap diisi dengan aksi unjuk rasa, seruan solidaritas, dan refleksi atas nasib kaum buruh.
Tapi kenapa tanggal 1 Mei yang dipilih?
Akar sejarah Hari Buruh Internasional bisa ditelusuri kembali ke akhir abad ke-19. Tepatnya pada tahun 1884 di Chicago, Amerika Serikat, ketika para pekerja mulai menyuarakan tuntutan untuk memperbaiki kondisi kerja yang kala itu sangat tidak manusiawi. Buruh bisa bekerja antara 10 hingga 16 jam per hari, namun upah yang diterima jauh dari layak. Tuntutan utama mereka saat itu: jam kerja dikurangi menjadi 8 jam per hari.
Puncaknya terjadi pada 1 Mei 1886. Ribuan buruh turun ke jalan melakukan aksi besar-besaran di berbagai kota industri, termasuk di Chicago. Aksi ini berubah menjadi tragedi saat terjadi bentrokan antara aparat dan demonstran, yang kemudian dikenal dengan insiden Haymarket Affair. Peristiwa ini menjadi simbol perjuangan buruh dan menggema hingga ke berbagai belahan dunia.
Tiga tahun kemudian, pada tahun 1889, Konferensi Sosialis Internasional yang digelar di Paris menetapkan 1 Mei sebagai Hari Buruh Internasional, sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan dan pengorbanan para buruh di Haymarket.
Di Indonesia sendiri, jejak peringatan Hari Buruh punya dinamika yang cukup panjang. Pada masa penjajahan, buruh Indonesia turut terinspirasi oleh gerakan buruh internasional, termasuk aksi mogok yang dilakukan oleh buruh kereta api. Tahun 1918 mencatat gelombang aksi besar dari para pekerja yang kecewa karena upah yang tidak memadai dan eksploitasi lahan milik buruh oleh penguasa kolonial.
Setelah kemerdekaan, pada 1 Mei 1946, pemerintah Indonesia melalui Kabinet Sjahrir secara resmi memberikan ruang bagi peringatan Hari Buruh. Namun situasinya berubah drastis di era Orde Baru. Pemerintah saat itu melarang peringatan Hari Buruh dan mengganti istilah “buruh” menjadi “karyawan”, upaya untuk meredam gerakan serikat pekerja yang dianggap mengganggu stabilitas politik.
Baru setelah Reformasi, kebebasan berserikat dan menyuarakan hak kembali dibuka. Presiden BJ. Habibie mengambil langkah penting dengan meratifikasi Konvensi ILO Nomor 81 tentang kebebasan berserikat. Dan akhirnya, pada tahun 2013 di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, 1 Mei resmi ditetapkan sebagai hari libur nasional.
Hari Buruh bukan sekadar hari libur. Ia adalah simbol perlawanan, solidaritas, dan harapan bagi kehidupan kerja yang lebih adil.
Jejak Panjang Hari Buruh Internasional yang Diperingati Setiap 1 Mei
Setiap tanggal 1 Mei, dunia memperingati Hari Buruh Internasional—sebuah momentum global untuk mengenang perjuangan kelas pekerja serta menyoroti persoalan kesejahteraan yang masih menjadi pekerjaan rumah hingga kini. Di berbagai negara, termasuk Indonesia, tanggal ini kerap diisi dengan aksi unjuk rasa, seruan solidaritas, dan refleksi atas nasib kaum buruh.
Tapi kenapa tanggal 1 Mei yang dipilih?
Akar sejarah Hari Buruh Internasional bisa ditelusuri kembali ke akhir abad ke-19. Tepatnya pada tahun 1884 di Chicago, Amerika Serikat, ketika para pekerja mulai menyuarakan tuntutan untuk memperbaiki kondisi kerja yang kala itu sangat tidak manusiawi. Buruh bisa bekerja antara 10 hingga 16 jam per hari, namun upah yang diterima jauh dari layak. Tuntutan utama mereka saat itu: jam kerja dikurangi menjadi 8 jam per hari.
Puncaknya terjadi pada 1 Mei 1886. Ribuan buruh turun ke jalan melakukan aksi besar-besaran di berbagai kota industri, termasuk di Chicago. Aksi ini berubah menjadi tragedi saat terjadi bentrokan antara aparat dan demonstran, yang kemudian dikenal dengan insiden Haymarket Affair. Peristiwa ini menjadi simbol perjuangan buruh dan menggema hingga ke berbagai belahan dunia.
Tiga tahun kemudian, pada tahun 1889, Konferensi Sosialis Internasional yang digelar di Paris menetapkan 1 Mei sebagai Hari Buruh Internasional, sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan dan pengorbanan para buruh di Haymarket.
Di Indonesia sendiri, jejak peringatan Hari Buruh punya dinamika yang cukup panjang. Pada masa penjajahan, buruh Indonesia turut terinspirasi oleh gerakan buruh internasional, termasuk aksi mogok yang dilakukan oleh buruh kereta api. Tahun 1918 mencatat gelombang aksi besar dari para pekerja yang kecewa karena upah yang tidak memadai dan eksploitasi lahan milik buruh oleh penguasa kolonial.
Setelah kemerdekaan, pada 1 Mei 1946, pemerintah Indonesia melalui Kabinet Sjahrir secara resmi memberikan ruang bagi peringatan Hari Buruh. Namun situasinya berubah drastis di era Orde Baru. Pemerintah saat itu melarang peringatan Hari Buruh dan mengganti istilah “buruh” menjadi “karyawan”, upaya untuk meredam gerakan serikat pekerja yang dianggap mengganggu stabilitas politik.
Baru setelah Reformasi, kebebasan berserikat dan menyuarakan hak kembali dibuka. Presiden BJ. Habibie mengambil langkah penting dengan meratifikasi Konvensi ILO Nomor 81 tentang kebebasan berserikat. Dan akhirnya, pada tahun 2013 di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, 1 Mei resmi ditetapkan sebagai hari libur nasional.
Hari Buruh bukan sekadar hari libur. Ia adalah simbol perlawanan, solidaritas, dan harapan bagi kehidupan kerja yang lebih adil.