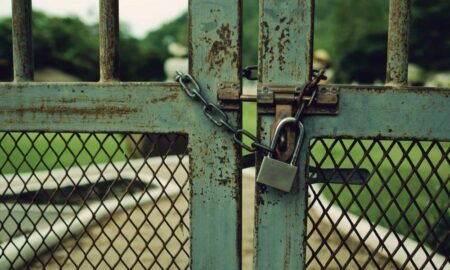Semangat yang Tertawakan
Puisi Chairil Anwar, “Aku mau hidup seribu tahun lagi,” menggambarkan perasaan yang dalam. Di satu sisi, api patriotisme menyala, tetapi di sisi lain, bara itu dipukul oleh realitas industri yang dingin dan tidak ramah terhadap idealisme. Film animasi “Merah Putih: One for All” adalah sebuah episode yang memperlihatkan wajah ganda dari semangat nasional. Ia hadir sebagai niat luhur untuk menghadirkan film patriotik di perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, namun berakhir dalam kontroversi, hujatan, dan ejekan.
Jagat maya Indonesia pada awal Agustus mendidih. Trailer “Merah Putih: One for All” beredar di platform digital, memicu ejekan sekaligus debat sengit. Publik mempermasalahkan kualitas animasi yang dianggap di bawah standar layar lebar. Biaya produksi disebut-sebut menelan lebih dari Rp6 miliar, angka fantastis jika dibandingkan dengan hasil visual yang dinilai jauh dari memadai. Sutradara sekaligus produsernya, Endiarto, bersikeras bahwa itu baru cuplikan; versi penuh di bioskop akan berbeda. Bahkan ia membantah kabar biaya produksi enam miliar tersebut, sembari mengungkapkan kenyataan pahit: para kru hanya dibayar dengan nasi goreng dan air mineral.
Kenyataan itu bagai pisau bermata dua. Di satu sisi, kita tertawa getir mendengar klaim yang seolah parodi dari dunia perfilman profesional. Namun di sisi lain, ada denyut keikhlasan yang mesti diakui: keberanian untuk berkarya dalam keterbatasan dana, waktu, dan tenaga—digerakkan oleh semangat merah putih, bukan oleh kalkulasi laba.
Idealisme yang Ditertawakan
“Sekali berarti, sudah itu mati.” Pernyataan Chairil Anwar ini menggambarkan perasaan banyak orang terhadap “Merah Putih: One for All.” Bagi banyak orang, film ini hanyalah tontonan gagal, sebuah bahan lelucon viral. Tetapi bila kita lepaskan kacamata sinis, justru yang tampak adalah semangat: idealisme tanpa pamrih, kerja yang lahir dari dada yang penuh cinta tanah air. Film ini diniatkan sebagai persembahan untuk HUT ke-80 Republik Indonesia, sebuah simbol kecil bahwa patriotisme dapat hidup di medium apapun, termasuk animasi.
Sayangnya, idealisme yang lahir dari ketulusan itu terhantam oleh benteng eksklusivitas industri film Indonesia. Dunia perfilman kita masih berdiri di menara gading: produksi harus megah, kualitas harus sinematik, distribusi harus komersial, dan sponsor harus hadir. Mereka yang mencoba menempuh jalan berbeda—dengan dana minim, tenaga terbatas, tapi semangat menyala—seringkali dicemooh bahkan sebelum karyanya benar-benar dicicipi.
Apakah kita lupa bahwa sejarah perfilman Indonesia juga lahir dari keberanian serupa? Bahwa film pertama negeri ini, Loetoeng Kasaroeng (1926), dibuat oleh tangan-tangan amatir yang nekat mencoba kamera? Bahwa generasi Usmar Ismail dan Djamaluddin Malik memulai sinema nasional dengan peralatan seadanya, tapi dengan hati sebesar samudera.
“Merah Putih: One for All” memang jauh dari sempurna, tapi bukan itu soalnya. Soalnya adalah: mengapa kita selalu menertawakan idealisme yang miskin modal, alih-alih merangkul dan membimbingnya?
Patriotisme di Era Industri
“Kami ini hanya tulang-tulang berserakan, tapi adalah kepunyaanmu.” Pernyataan Chairil Anwar ini menjadi refleksi penting tentang patriotisme di era industri. Patrioteisme di layar lebar bukan sekadar hiburan, ia adalah refleksi identitas bangsa. Namun ironinya, film-film bertema patriotik sering kali hanya menjadi proyek sesaat: muncul menjelang hari-hari besar nasional, lalu hilang ditelan gemerlap film komedi romantis atau horor komersial.
“Merah Putih: One for All” mencoba keluar dari pola itu. Ia hadir bukan dari produser besar, bukan dari studio mapan, bukan pula dari jaringan sineas elite. Ia lahir dari komunitas kecil, dari semangat nekat yang ingin memberi hadiah ulang tahun untuk Indonesia. Tetapi alih-alih dirayakan sebagai upaya patriotis, film ini dihantam cemooh: dianggap proyek gagal, bahan lelucon, atau bahkan penipuan.
Kita lupa bahwa di balik semua kekurangan teknis, ada pesan yang lebih besar: patriotisme tanpa pamrih. Endiarto dan timnya bekerja tanpa sponsor swasta, tanpa dukungan negara, hanya berbekal cinta tanah air, nasi goreng dan air mineral—mungkin ada segelas kopi dan berbatang-batang rokok juga.
Bukankah ini sebuah ironi? Di negeri yang benderanya dikibarkan dengan darah dan air mata, sebuah karya patriotik justru dibiarkan terkapar sendirian. Mirisnya lagi, Upacara Bendera Kenegaraan ditutup dengan acara joget bersama—jauh dari rasa hikmat.
Eksklusivitas yang Membelenggu
Industri film Indonesia dalam dua dekade terakhir memang berkembang pesat. Dari segi jumlah produksi, kualitas visual, hingga pencapaian internasional, kita boleh berbangga. Tetapi di balik itu, ada tembok eksklusivitas yang semakin tebal.
Film-film yang bisa masuk jaringan bioskop besar umumnya hanya mereka yang lahir dari rumah produksi mapan, memiliki modal miliaran, didukung sponsor dan distribusi kuat. Sementara karya independen—apalagi dengan semangat patriotik—sering tersingkir di pinggir jalan.
Inilah tamparan keras yang diberikan oleh “Merah Putih: One for All.” Ia membuka borok industri film kita: betapa sulitnya karya kecil menemukan tempat di negeri sendiri. Betapa cepatnya publik menertawakan kekurangan teknis, tanpa mau memahami perjuangan yang tersembunyi di balik layar.
Seperti kata WS Rendra dalam Sajak Pertemuan Mahasiswa: “Kita bertanya, Maksud baik untuk siapa?” Katanya, “kritik pedas terhadap film ini memiliki maksud yang baik.” Tapi industri film kita lebih sibuk menghitung laba, sibuk mengejar festival, sibuk mengoleksi penghargaan. Dan ketika ada yang datang dengan semangat ikhlas, membawa merah putih sebagai bendera, ia justru ditolak mentah-mentah.
Dukungan yang Hampa
Pertanyaan terbesar adalah: di mana negara? Di mana perusahaan-perusahaan besar yang kerap mengibarkan slogan nasionalisme di iklan-iklan mereka? Mengapa ketika ada film patriotik lahir dari rakyat kecil, mereka memilih diam atau terlalu sibuk mengotak-atik anggaran untuk menaikan tunjangan?
Tidak cukupkah pengalaman kita melihat bagaimana Korea Selatan mendukung industri filmnya hingga menembus dunia? Pemerintahnya tidak hanya memberi insentif pajak, tapi juga subsidi produksi, dukungan distribusi, bahkan promosi global. Hasilnya? Film “Parasite” (2019) mengguncang Oscar, “Squid Game” (2021) merajai Netflix, dan film-film patriotik mereka tidak pernah sepi penonton.
Indonesia justru sibuk dengan wacana, dengan janji-janji yang tak pernah terealisasi. Dukungan negara hanya hadir pada proyek-proyek besar yang dikerjakan sineas elite yang mukanya itu-itu saja, sementara mereka yang berjuang dari pinggiran dibiarkan. Hal ini jauh dari karakter inklusif. Apakah merah putih hanya simbol di bendera? Ataukah ia seharusnya juga menjadi nafas dalam industri kreatif bangsa?
Seruan untuk Kebersamaan
“Bersatu seperti baja tempa: api yang menghidupkan senja.” Merah Putih: One for All seharusnya menjadi momentum refleksi, bukan sekadar bahan tertawaan. Ia mengingatkan kita bahwa industri film Indonesia sedang sakit, terjebak dalam eksklusivitas dan melupakan roh kebangsaan.
Kita perlu membangun ekosistem yang lebih inklusif: Pemerintah harus hadir dengan kebijakan yang mendukung film patriotik, bukan sekadar mengucurkan dana untuk proyek seremonial. Swasta perlu melihat film patriotik sebagai investasi moral dan sosial, bukan sekadar bisnis. Masyarakat mesti belajar menghargai semangat, bukan hanya hasil akhir. Kritik boleh, tapi jangan lupa merangkul.
Karena bangsa ini tidak dibangun oleh kesempurnaan, melainkan oleh keberanian untuk mencoba. Dan selalu bangkit dari kegagalan.
Penutup: Merah Putih, Untuk Semua
“Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya.” W.R. Supratman, lagu “Indonesia Raya”.
Merah putih adalah milik semua. Ia bukan monopoli sineas besar, bukan pula hak istimewa studio elit. Ia adalah bendera yang harus kita kibarkan bersama, di layar lebar maupun di layar kecil, di panggung besar maupun di ruang yang sepi.
“Merah Putih: One for All” adalah sebuah tamparan bagi kita semua. Ia mengingatkan patriotisme tidak boleh eksklusif. Bahwa industri film Indonesia harus membuka diri, merangkul idealisme, mendukung semangat tanpa pamrih, agar kelak lahir karya-karya besar yang bukan hanya indah dipandang, tapi juga menggetarkan jiwa bangsa.
Pada akhirnya, mungkin film itu memang jauh dari sempurna. Tetapi bukankah merah putih sendiri lahir dari darah dan air mata, dari luka dan cacat, dari keberanian yang sering ditertawakan lawan?
Maka mari kita belajar dari kisah ini: jangan biarkan semangat patriotik mati hanya karena kita terlalu sibuk menertawakan kekurangan. Sebab bila semangat itu padam, maka bukan hanya satu film yang gagal. Namun yang gagal adalah kita semua: sebagai bangsa dan sebagai negara. Merdeka!