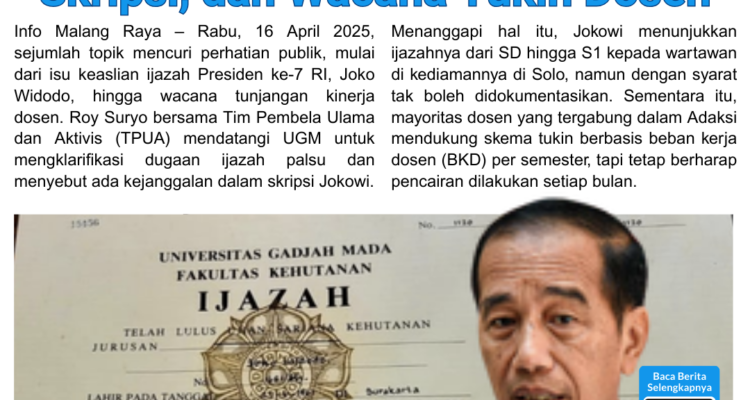Infomalangraya.com –
Pada tanggal 3 April, berbicara kepada delegasi anggota parlemen dari lebih dari 22 negara Afrika, yang telah menghadiri konferensi tentang “nilai-nilai dan kedaulatan keluarga” di Entebbe, Presiden Uganda Yoweri Museveni meminta para pemimpin benua untuk menyelamatkan dunia dari homoseksualitas.
Dalam pidatonya, Museveni – pendukung lama terapi konversi, praktik ilmu semu untuk mencoba mengubah orientasi seksual atau ekspresi gender seseorang – mengklaim bahwa homoseksualitas adalah “dapat dibalik dan disembuhkan”.
Belum lama ini, saya akan mendukung pernyataan berbahaya dan tidak berdasar ini dan akan mendukung RUU kontroversial anti-LGBTQ yang disahkan oleh parlemen Uganda pada bulan Maret. Undang-undang mengusulkan hukuman mati untuk tindakan homoseksual tertentu dan hukuman penjara seumur hidup untuk “perekrutan, promosi dan pendanaan” dari “kegiatan” sesama jenis. Ini melarang orang Uganda mengidentifikasi sebagai lesbian, gay, biseksual, transgender atau queer (LGBTQ).
Saya tidak terlahir sebagai homofobia, tetapi selama bertahun-tahun membenci komunitas LGBTQ.
Sebagai seorang mahasiswa di Universitas Cape Town, saya memiliki beberapa perselisihan dengan seorang rekan gay yang ramah dan terang-terangan mengenai seksualitasnya. Meskipun hubungan sesama jenis didekriminalisasi melalui konstitusi pasca-apartheid Afrika Selatan pada tahun 1996, saya tidak tahan melihat dia jujur pada karakter dan seksualitasnya.
Untuk seseorang yang dibesarkan di Harare, Zimbabwe – sebuah masyarakat konservatif di mana homoseksualitas telah lama dianggap ilegal menurut hukum – keluarga dan teman-teman memandang ketidaksenangan saya terhadap pria dan wanita gay sebagai hal yang normal.
Saya disosialisasikan untuk percaya bahwa lesbian dan gay adalah kutukan bagi keluarga alami, takut akan Tuhan dan tradisional yang harus dicita-citakan oleh setiap pria dan wanita.
Presiden kita saat itu, Robert Mugabe, sering mengatakan bahwa orang Zimbabwe (dan orang Afrika) memiliki nilai moral yang kuat sedangkan orang Barat, yang mengizinkan homoseksualitas, jelas tidak bermoral. Sementara itu, dia menyamakan homoseksualitas dengan bestialitas di setiap kesempatan dan memohon kepada gereja untuk mengkhotbahkan homofobia dalam khotbahnya.
Tidaklah mengherankan bahwa segerombolan mahasiswa dari Universitas Zimbabwe menggeledah stan milik Asosiasi Gay dan Lesbian (GALZ) Zimbabwe di Pameran Buku Internasional Zimbabwe pada tahun 1996. Kebanyakan orang – termasuk saya sendiri – mendukung perilaku kekerasan dan tidak dapat diterima mereka .
Dalam pikiran kami yang diindoktrinasi, GALZ adalah protagonis yang bersalah dan nakal, karena itu menguji tekad bersama kami untuk mempertahankan budaya dan negara kami dari kekejian yang mengganggu dan agenda asing yang jahat.
Saya masih muda, mudah dipengaruhi dan jatuh cinta, garis dan pemberat untuk oposisi yang dibuat-buat terhadap inklusivitas sosial yang meluas. Saya juga gagal melihat bahwa Mugabe menggunakan homofobia sebagai tipu muslihat politik – bahkan ketika sekutunya, mantan Presiden Zimbabwe Canaan Banana, pada tahun 1997 dihukum karena memaksa seorang ajudan melakukan hubungan homoseksual selama tiga tahun.
Hari ini, untungnya, saya bangga bahwa saya tidak lagi fanatik. Saya telah membuang mentalitas saya yang dulu beracun dan berpikiran sempit. Saya berharap saya dapat menyampaikan permintaan maaf yang telah lama tertunda dan sepenuh hati kepada mantan kolega saya di University of Cape Town. Keyakinan tradisional dan Gereja Anglikan saya tidak lagi memengaruhi perasaan dan perilaku saya terhadap orang-orang LGBTQ. Saya mencintai dan merangkul mereka sebagai keluarga, sebagai sesama orang Afrika yang saleh, yang berhak atas hak asasi manusia dan kesempatan yang sama dalam hidup.
Tetapi di sekitar Afrika, sayangnya, homofobia yang dipimpin oleh negara sedang meningkat. Politisi dan pemimpin agama terus mencirikan homoseksualitas sebagai kejahatan asing. Pencarian pascakolonial yang tidak berperasaan dan tidak hati-hati untuk menyusun keistimewaan budaya dan moral ini telah menyebabkan upaya untuk menolak dan menahan kehadiran homoseksual yang sudah berlangsung lama di masyarakat Afrika.
Di Tanzania, pemerintah telah melarang sekolah sejumlah buku yang memiliki konten terkait LGBTQ karena diduga melanggar norma budaya setempat. Di negara tetangga Kenya, sementara itu, Presiden William Ruto memobilisasi penentangan publik terhadap putusan Mahkamah Agung yang mengizinkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Gay dan Lesbian (NGLHRC) untuk mendaftar sebagai sebuah LSM.
Dan RUU anti-LGBTQ ekstrem yang disahkan pada bulan Maret oleh parlemen Uganda, menurut LSM global Human Rights Watch, memperkuat kriminalisasi perilaku sesama jenis. Untuk saat ini, Museveni belum menandatangani RUU tersebut – dia setuju dengan hukuman tersebut, kata juru bicaranya, tetapi tampaknya menginginkan lebih banyak belas kasih ditunjukkan kepada mereka yang telah terlibat dalam homoseksualitas “di masa lalu” dan sekarang ingin menjalani “kehidupan normal kembali”. .
Sama seperti Mugabe di Zimbabwe, Museveni telah membingkai homoseksualitas sebagai ancaman eksistensial terhadap kemanusiaan untuk mengalihkan perhatian publik dari kepemimpinannya yang gagal dan tidak liberal, yang telah membuat rakyat Uganda bergulat dengan meningkatnya kemiskinan dan pelanggaran hak.
Di bawah pengawasannya, Red Pepper, sebuah surat kabar yang berbasis di Kampala, menerbitkan daftar “200 Homoseksual Teratas” Uganda pada tahun 2014, tindakan memalukan dan jahat yang membahayakan mata pencaharian berharga dan kehidupan orang-orang tak bersalah. Di bawah pemerintahan Museveni, aktivis LGBTQ seperti David Kato dan Brian Wasswa telah dibunuh.
Dan seperti Mugabe, skema politik Museveni memproyeksikan homoseksualitas sebagai plot yang diangkut ke Afrika dari negara-negara bekas jajahan — poin yang dia ulangi pada bulan Maret dalam pidato State of the Nation. “Negara-negara Barat harus berhenti menyia-nyiakan waktu kemanusiaan dengan mencoba memaksakan praktik mereka pada orang lain,” katanya.
Jelasnya, kolonialisme berakhir beberapa dekade yang lalu – tepatnya pada tahun 1962, untuk Uganda.
Tidak ada alasan yang masuk akal untuk mempertimbangkan inklusivitas seksual dan gender dalam masyarakat Afrika melalui prisma moralitas Barat yang jauh dan tidak penting.
Anggota komunitas LGTBQ di Afrika, yang lahir dan dibesarkan oleh pria dan wanita Afrika, bukanlah manusia atau Afrika yang lebih rendah dari Museveni. Semua orang Afrika – termasuk individu heteroseksual, homoseksual, atau aseksual – harus bebas mengekspresikan diri mereka tanpa melanggar standar moral dan hukum yang aneh yang bertentangan dengan norma dan keinginan manusia yang abadi.
Gambaran terbatas dan sebelumnya tentang nilai-nilai keluarga dan keluarga, seperti yang dianut oleh orang-orang seperti Museveni, jelas salah dan ketinggalan zaman.
Pada awal April, Sarah Opendi, ketua Asosiasi Parlemen Wanita Uganda, yang sering terdengar seperti klon Museveni yang bertele-tele, menyatakan, “Kami ingin semua orang Afrika, pemimpin tradisional, pemimpin agama, dan legislator memastikan bahwa kami mempromosikan nilai-nilai Afrika kami” .
Di masa lalu, saya secara keliru menganut pandangan seperti itu.
Sekarang, saya tahu bahwa sebuah keluarga bukanlah konstruksi sosial yang tidak fleksibel yang terbatas pada heteroseksual, tetapi manifestasi cinta, komitmen, dan kebahagiaan yang kuat dan mendasar yang terbuka untuk semua.
Afrika harus merangkul semua orangnya yang cantik dan membiarkan komunitas LGBTQ berkembang. Jika ada yang pantas ditolak, itu adalah orang-orang seperti Museveni.
Pandangan yang diungkapkan dalam artikel ini adalah milik penulis dan tidak mencerminkan sikap editorial Al Jazeera.