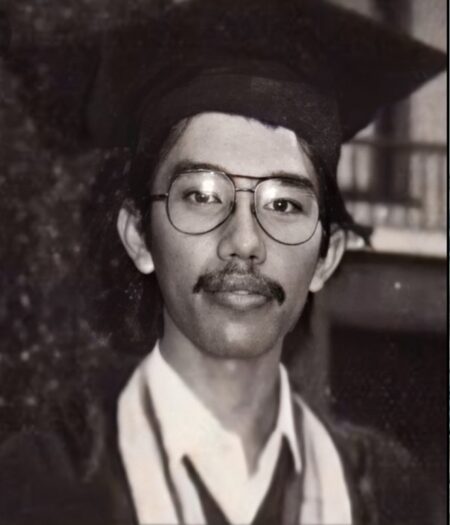Program ‘gentengisasi’ yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto mendapat berbagai tantangan, baik dari sisi teknis kebencanaan maupun keberlanjutan. Selain itu, banyak pengamat menilai bahwa bentuk rumah-rumah di Indonesia memiliki karakteristik yang beragam dan tidak bisa diseragamkan. Pertanyaannya adalah, siapa yang benar-benar diuntungkan dalam program ini?
Pada Januari lalu, saat mengunjungi hunian sementara (huntara) di Aceh Tamiang, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kekhawatiran terhadap atap bangunan yang terbuat dari seng, yang membuat ruangan menjadi sangat panas.
“Ini kan seng panas, coba dipikirkan kalau bisa kita kasih solusi,” kata Presiden Prabowo dalam rapat bersama sejumlah menteri, masih di Aceh Tamiang.
Sebulan kemudian, wacana tentang penggantian atap rumah yang terbuat dari seng muncul kembali. Kali ini dalam bentuk gagasan pembuatan program nasional ‘gentengisasi’.
“Seng ini panas untuk penghuni. Seng ini juga berkarat jadi tidak mungkin Indonesia indah kalau semua genting [atap] dari seng,” ujar Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya dalam acara Taklimat Presiden RI pada Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul, Jawa Barat, Senin (02/02).
Genting tanah liat dinilai cocok digunakan di wilayah Indonesia yang beriklim tropis karena mampu meredam panas. Namun, dalam aspek teknis khususnya bencana seperti gempa bumi, lain ceritanya.
Genting yang berupa lembaran, mudah terpisah jika terjadi gempa bumi. “Mudah terpisah-pisah dan massanya berat, maka beban yang ditanggung oleh struktur atap maupun bangunannya juga semakin besar,” jelas Ashar Saputra, dosen Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan, Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta.

Gempa bumi dengan magnitudo 6.4 di Bantul dan Pacitan pada Jumat (06/02) pukul 01.06 WIB dalam catatan BNPB menyebabkan empat rumah terdampak. Salah satu dampaknya, kerusakan atap genting tanah liat.
“Bukannya tidak boleh memasang genting tanah liat, tetap memungkinkan, tetapi harus dipertimbangkan kesesuaian struktur atap dan bangunan,” jelas Ashar.
Dia menambahkan, atap berupa lembaran seperti seng tidak terlalu sensitif terhadap gempa karena massanya ringan. “Sehingga, dalam aspek gempa, atap yang ringan tidak berupa potongan-potongan seperti genting, akan mengurangi risiko dampak gempa,” tambah Ashar.
Jika ‘gentengisasi’ diimplementasikan secara nasional, Ashar menilai, ada risiko lain yang perlu diwaspadai, yaitu memasang genting yang berat, tetapi strukturnya tidak disiapkan untuk menerima beban berat itu.
Ashar mencontohkan kejadian ruang kelas di SMKN 1 Gunung Putri, Kabupaten Bogor pada November 2025 lalu, yang roboh karena hujan deras. Terlihat baja ringan dalam struktur atap, yang menurut Ashar menjadi penyebab runtuhnya atap bangunan.

Baja ringan atau baja canai dingin merupakan bahan bangunan yang sedang populer karena harganya yang relatif terjangkau. “Pengerjaannya cukup cepat, tetapi jadi rawan jika konstruksinya tidak baik, kemudian menerima beban genting yang berat,” jelas Ashar.
Dalam sejumlah kasus atap roboh, menurut Ashar, penyebabnya adalah penggunaan baja ringan sebagai konstruksi atap. Jadi, ‘gentengisasi’ tidak hanya tentang gentingnya saja. Bukan pula estetika semata.
“Kalau mengatasi masalah estetika akibat seng karatan, seolah daerah itu menjadi kumuh, kemudian langsung melompat serta-merta menggantinya dengan genting, itu kan sepenuhnya tidak nyambung,” ujar Ashar.
Ashar merekomendasikan untuk menggunakan material lain yang tersedia. Dia mencontohkan atap uPVC (un-Plasticized Polyvinyl Chloride) dan bitumen atau atap ringan yang terbuat dari campuran selulosa dan aspal. Kedua material itu bisa meredam panas matahari, seperti yang dikeluhkan oleh Presiden Prabowo, terutama tetap terlihat ‘estetik’.

Selain aspek teknis, aspek budaya pun harus dipertimbangkan dalam ‘gentengisasi’, menurut Dosen Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan, Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Ashar Saputra.
Sebenarnya unsur budaya sudah disadari oleh presiden pada 1 Januari 2026 lalu. Presiden Prabowo Subianto sempat melontarkan solusi mengatasi atap seng yang panas di huntara, Aceh Tamiang. “Mungkin kita bisa pakai bahan-bahan lokal,” ujarnya.
Bahan lokal seperti memang digunakan untuk bahan atap sejumlah bangunan yang bentuknya beragam di Indonesia. Beberapa rumah tradisional, seperti Rumah Gadang di Sumatera Barat, Tongkonan di Toraja, atau rumah adat di Nias dan Papua, memiliki karakteristik tersendiri dalam bentuk atapnya.
Secara historis, bentuk tersebut memungkinkan penggunaan material seperti ijuk atau sirap yang lentur dan mudah dibentuk. Ashar mencontohkan Rumah Gadang. Dahulu rumah-rumah gadang beratap bahan lokal, hingga pada akhirnya kini banyak menggunakan seng.
“Bahan itu mudah meliuk mengikuti lekukan atap bangunan rumah gadang, terlebih atap seng lebih mudah perawatannya” kata Ashar.

Nilai kearifan lokal penggunaan bahan atap juga tak bisa dilupakan. Budayawan Minangkabau, Viveri Yudi, atau akrab disapa Mak Kari menyebut, jika menggunakan genting dibuat dari tanah maka tanah dikeruk dari bukit, “itu akan merusak alam.”
“Kami memakai atap seng sebagai kemajuan teknologi, sepanjang itu tidak merusak alam sekitar, dalam artian konteks lokal,” kata Mak Kari kepada Halbert Chaniago, wartawan di Kota Padang, Sumatra Barat.
Terlebih, sebagai wilayah rawan gempa, Mak Kari menyebut nenek moyang orang Minang paham betul penggunaan material yang ringan sebagai atap bangunan. “Kelompok masyarakat adat di Indonesia punya kearifan lokal hasil dari interaksi dan adopsi dengan lingkungannya, itu yang harus dipahami, jangan sampai diseragamkan,” tambah Mak Kari.
Senada dengan Mak Kari, Ashar menilai, jika menggunakan genteng yang berat dan kaku akan menjadi tantangan tersendiri dan berpotensi menghilangkan karakter asli bangunan tradisional.

Siapa yang diuntungkan dalam ‘gentengisasi’? Selain aspek teknis dan budaya, satu aspek lagi yang harus dipertimbangkan adalah aspek keberlanjutan.
Ashar mengatakan, dalam ilmu material bangunan, pemilihan material seharusnya mempertimbangkan energi yang dibutuhkan sejak proses produksi hingga penggunaannya.
Masih di Sumatra Barat, tidak ada produsen genting tanah liat di Pulau Siberut di Kepulauan Mentawai. Sebagian rumah di desa-desa yang sulit dijangkau, sebagian beratap daun sagu dan seng, termasuk di Desa Matotonan, terletak di rimba Siberut dan hanya bisa diakses melalui sungai dengan perahu kecil.
Rumah-rumah di desa ini merupakan rumah panggung kayu beratap daun sagu kering. “Sekarang banyak rumah yang beratap seng,” ujar Sabarial, warga Desa Matotonan.
Atap seng itu merupakan bentuk kepedulian pemerintah setempat ketika membangun rumah-rumah warga Desa Matotonan 2006 lalu. Namun, menurut Sabarial, jika suatu saat atap seng di rumahnya diganti dengan genting dalam ‘gentengisasi’, maka yang terjadi, dia dan keluarganya harus memastikan rumah kayunya kuat menopang genting tanah liat.
“Alih-alih pikir rumah terlebih dahulu, cara bawa genting itu ke desa kami juga sulit,” tambahnya.
Dengan akses yang terbatas itu, menurut Sabarial, ‘gentengisasi’ mustahil diterapkan di desanya, kecuali mau bolak-balik naik perahu puluhan kali membawa genting dan bahan material berat lainnya dengan perahu yang hanya muat untuk setidaknya empat orang.
“Biaya transportasi untuk bahan bakar perahu pasti membengkak, itu baru dari jalur sungai, belum lagi, sebelum itu, membawa genting-genting itu menuju pulau, entah dari Pulau Sumatra, atau Jawa.” Sehingga, warga dengan rumah beratap seng seperti Sabarial, tidak diuntungkan dalam ‘gentengisasi’.
Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahardiansah, menilai, ‘gentengisasi’ jelas menguntungkan produsen-produsen genting di Pulau Jawa. “Ketika produksinya meningkat, tentu akan menyerap tenaga kerja yang banyak,” tambahnya.
Jika program ini berlaku secara nasional, akan tumbuh produsen-produsen baru yang bisa menciptakan industri, dan pada akhirnya korporasi yang diuntungkan. “Yang punya kapasitas produksi untuk memenuhi permintaan ‘gentengisasi’ itu korporasi, setidaknya yang memiliki modal.” Termasuk untuk mendatangkan genting tanah liat dari sentra produksi seperti di Pulau Jawa menuju wilayah lain di Indonesia yang tidak memiliki tempat produksi genting.
Trubus memandang, ‘gentengisasi’ yang mengedepankan konteks estetika dan kerapihan yang diucapkan Presiden Prawowo itu erat kaitannya dengan pariwisata. Dalam pidato presiden pada 2 Februari lalu, ‘gentengisasi’ merupakan bagian dari agenda penataan lingkungan yang lebih luas, termasuk pengelolaan sampah, penertiban papan reklame dan baliho, serta penataan kabel-kabel di kawasan perkotaan.
Genting tanah lempung yang seragam dapat menciptakan lanskap yang estetik di suatu tempat, berpotensi mendatangkan turis. “Jika begitu, pihak yang diuntungkan adalah pelaku industri pariwisata,” imbuh Trubus.