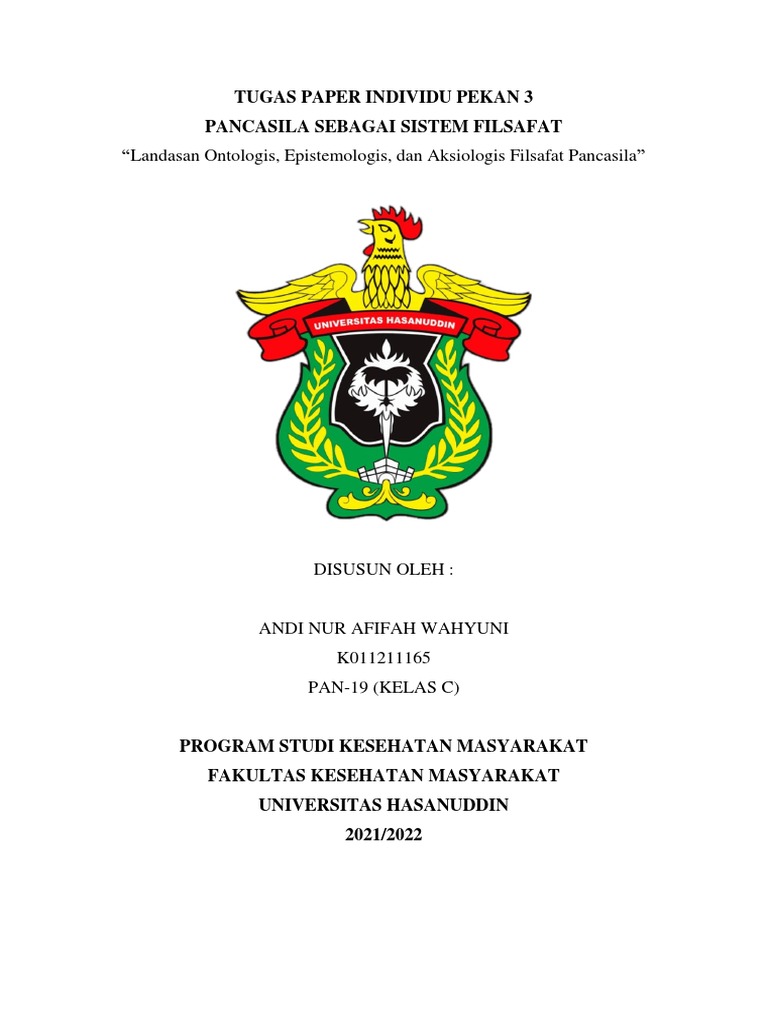Oleh: Aldo el-Haz Kaffa (Coach Kaffa)
Presiden Islamic Lombok Forum, CEO Kaffa Business Coach, Entrepreneurial Mindset Mainstreamer, Mindset is Everything.
Menyebut Islam sebagai sistem hidup bukanlah pernyataan retoris, apalagi slogan apologetik. Ia adalah sebuah klaim epistemologis dan ontologis yang sangat serius. Klaim ini menempatkan Islam bukan sekadar sebagai agama dalam pengertian privat—yang berhenti di ruang ibadah dan batin personal—melainkan sebagai kerangka berpikir komprehensif tentang realitas, manusia, nilai, dan tujuan hidup.
Dalam terminologi filsafat ilmu, Islam mengajukan diri sebagai worldview: seperangkat asumsi dasar tentang apa yang dianggap nyata, benar, baik, dan bermakna. Setiap peradaban besar dalam sejarah manusia berdiri di atas worldview semacam ini, baik disadari maupun tidak. Modernitas Barat, misalnya, berdiri di atas rasionalisme, empirisisme, dan sekularisme; sementara Islam berdiri di atas tauhid sebagai prinsip pemersatu seluruh realitas.
Di sinilah letak kesalahpahaman mendasar sebagian kalangan—termasuk di kalangan muslim terdidik sendiri. Islam sering dipersempit menjadi kumpulan hukum ibadah atau simbol identitas, padahal ia sejak awal hadir sebagai arsitektur nilai yang menata keseluruhan kehidupan. Reduksi inilah yang kemudian melahirkan kesan bahwa Islam tidak relevan, ketinggalan zaman, atau tidak kompatibel dengan kompleksitas modern.
Padahal, yang sering tidak kompatibel bukan Islamnya, melainkan cara pandang kita yang terfragmentasi—membaca Islam secara parsial, ahistoris, dan lepas dari kerangka besarnya.
Argumentasi Fitrah Manusia
Islam tidak mengklaim universalitas secara emosional, tetapi secara argumentatif. Al-Qur’an tidak diturunkan untuk satu etnis atau kelas sosial tertentu, melainkan خطابًا للناس (khithāban lin-nās): seruan kepada manusia sebagai manusia. Universalitas ini tidak bersandar pada keseragaman budaya, melainkan pada kesamaan fitrah.
Fitrah manusia—kebutuhan akan makna, keadilan, keteraturan, dan kasih sayang—adalah konstanta antropologis. Teknologi boleh berubah, sistem politik boleh berganti, tetapi kegelisahan eksistensial manusia tetap sama. Di sinilah Islam menemukan relevansi lintas zaman: bukan karena ia fleksibel tanpa prinsip, tetapi karena ia selaras dengan struktur terdalam kemanusiaan.
Bagi kalangan intelektual, argumen fitrah ini penting. Ia menunjukkan bahwa Islam tidak bekerja dengan logika paksaan atau indoktrinasi, tetapi dengan resonansi batin. Islam tidak memusuhi akal; ia justru mengajaknya bekerja sampai ke batas terdalamnya—hingga akal itu sendiri mengakui keterbatasannya dan membutuhkan panduan nilai.
Nabi Muhammad Bukti Historis Sistem Islam
Salah satu keunggulan metodologis Islam adalah keberanian historisnya. Islam tidak hanya berkata “inilah yang benar”, tetapi juga menunjukkan contoh empiris bagaimana kebenaran itu dijalankan. Kehadiran Nabi Muhammad shalallahu ‘alayhi wasallam bukan sekadar figur spiritual, tetapi model operasional dari sistem Islam.
Dalam istilah ilmu sosial kontemporer, Nabi adalah living model—sebuah eksperimen historis yang berhasil. Nilai-nilai Islam tidak berhenti sebagai norma ideal, tetapi terwujud dalam praktik: dalam kepemimpinan politik yang beretika, dalam relasi sosial yang berkeadilan, dalam ekonomi yang berorientasi maslahat, dan dalam pendidikan yang membebaskan manusia dari kebodohan dan penindasan.
Bagi sarjana muslim, ini adalah data epistemologis yang sangat penting. Islam bukan utopia. Ia pernah dijalankan, dalam kondisi sosial yang kompleks, dengan hasil yang terukur secara sejarah. Maka, meragukan kemungkinan penerapan Islam hari ini tanpa mengkaji keberhasilan historisnya adalah kelalaian akademik, bukan skeptisisme ilmiah.
Relevansi Islam dan Kesalahan Paradigma Modern
Modernitas sering mengklaim diri sebagai puncak rasionalitas manusia. Namun jika ditelaah lebih dalam, banyak krisis modern justru lahir dari hilangnya panduan nilai. Kemajuan teknologi tanpa etika melahirkan eksploitasi; kebebasan tanpa tanggung jawab melahirkan kekacauan; rasionalitas tanpa moralitas melahirkan dehumanisasi.
Islam hadir bukan untuk menolak kemajuan, tetapi untuk memberi arah. Ia menolak absolutisasi akal, bukan penggunaan akal. Ia membatasi kebebasan, bukan mematikannya. Dalam bahasa yang lebih tegas: Islam tidak anti-modern, tetapi anti-kehilangan-makna.
Menyesuaikan Islam agar diterima zaman—dengan mengorbankan prinsip-prinsip dasarnya—adalah bentuk intelektual insecurity. Sebaliknya, menantang zaman dengan nilai-nilai Islam adalah tanda kepercayaan diri peradaban.
Amanah Kaum Intelektual Muslim
Di sinilah amanah kaum intelektual muslim menjadi krusial. Ilmu bukan sekadar alat mobilitas sosial, tetapi beban etik. Semakin tinggi ilmu seseorang, semakin besar tanggung jawabnya untuk menghadirkan Islam secara dewasa, jernih, dan bermartabat.
Islam tidak membutuhkan pembela yang berisik, tetapi pemikir yang jujur. Yang berani mengakui kompleksitas, yang tidak takut pada kritik, dan yang tidak tergoda mereduksi Islam demi popularitas atau kenyamanan sosial.
Kaum intelektual muslim dipanggil untuk menjadi jembatan: antara teks dan konteks, antara prinsip dan realitas, antara iman dan kemanusiaan universal. Dakwah mereka bukan lewat mimbar semata, tetapi lewat integritas berpikir dan keteladanan hidup.
Pluralitas, Tauhid, dan Kedewasaan Beragama
Islam yang dipahami secara sistemik tidak akan melahirkan paranoia terhadap perbedaan. Tauhid yang matang justru melahirkan ketenangan eksistensial. Seorang muslim yang yakin pada kebenaran Islam tidak perlu gelisah melihat keberagaman; ia tahu bahwa kebenaran tidak membutuhkan kekerasan untuk bertahan.
Keberadaan non-muslim bukan ancaman, tetapi cermin. Di hadapan merekalah Islam diuji: apakah ia hadir sebagai rahmat, atau sebagai identitas yang kaku dan defensif. Pertanyaan ini bersifat praksis, bukan teoretis. Ia dijawab melalui keadilan, kejujuran, empati, dan keberpihakan pada yang lemah.
Menuju Penanggung Jawab Peradaban
Islam telah sempurna sebagai sistem nilai. Nabi telah mencontohkan penerapannya. Sejarah telah mengujinya. Maka problem kita hari ini bukan kekurangan ajaran, melainkan kekurangan keberanian intelektual untuk hidup sesuai ajaran itu secara utuh.
Pertanyaannya kini tidak lagi: apakah Islam relevan? Tetapi: apakah kita siap memikul konsekuensinya?
Menjadi muslim intelektual berarti siap naik kelas—dari pengamat menjadi pelaku, dari komentator menjadi penjaga arah, dari pewaris wacana menjadi penanggung jawab peradaban.
Dan di titik itulah, Islam tidak lagi sekadar diyakini. Ia dihidupi.