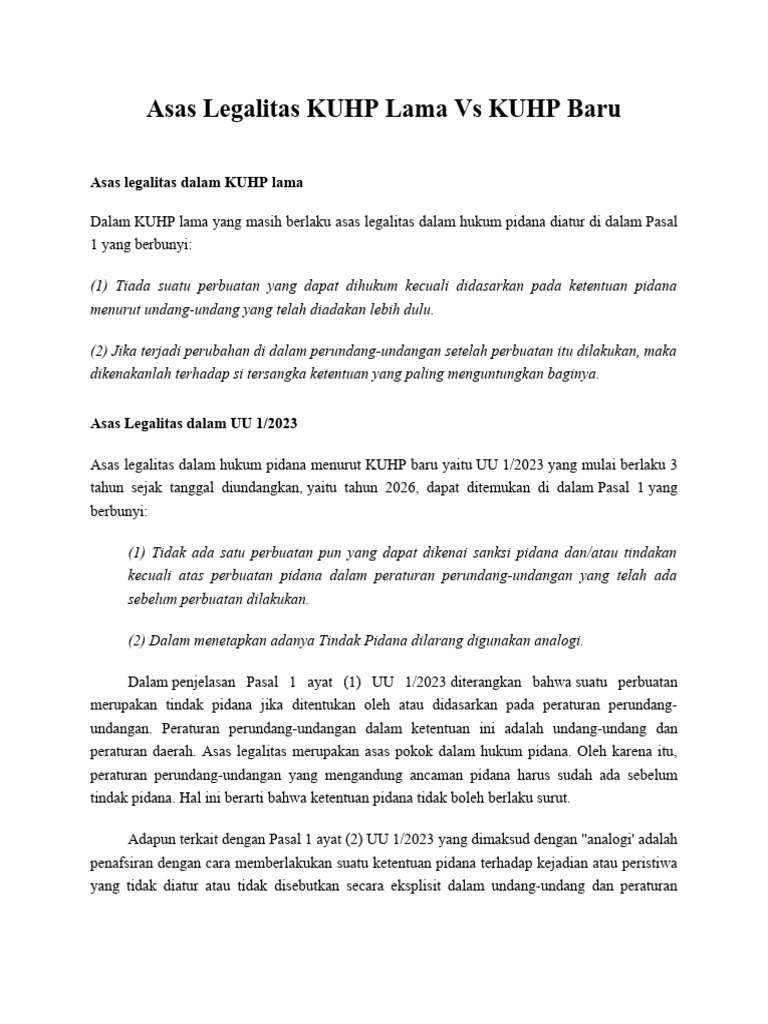Perkawinan dan Kepatuhan Hukum dalam Era KUHP Baru
Selama berpuluh-puluh tahun, frasa “yang penting sah di mata Tuhan” telah menjadi pelindung moral bagi praktik nikah siri dan poligami di bawah tangan di tengah masyarakat kita. Namun, sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), “benteng” spiritual tersebut tidak lagi cukup untuk menghindarkan pelakunya dari terali besi.
Negara telah mengetuk palu: perkawinan bukan lagi sekadar urusan privat atau kesepakatan di atas sajadah, melainkan sebuah peristiwa hukum yang wajib tunduk pada tertib administrasi. Jika tidak, penjara hingga 6 tahun kini menanti di ujung jalan.
Secara akademis, lahirnya Bab XIV KUHP Baru mengenai Tindak Pidana Terhadap Asal-Usul dan Perkawinan merupakan sebuah revolusi hukum. Jika sebelumnya pelanggaran terhadap syarat perkawinan lebih banyak diselesaikan di ranah perdata melalui pembatalan nikah di Pengadilan Agama, kini negara memberikan taring pada aturan tersebut melalui instrumen pidana.
Pasal 402 hingga 405 KUHP Baru menjadi manifestasi ketegasan negara. Pesannya lugas: siapa pun yang mencoba mengakali hukum perkawinan nasional, akan berhadapan dengan penyidik kepolisian, bukan sekadar teguran administratif dari kantor urusan agama.
Salah satu poin paling krusial yang harus dipahami oleh masyarakat adalah pengetatan aturan poligami. Dalam hukum nasional kita (UU Perkawinan No. 1/1974), poligami adalah pintu darurat yang hanya bisa dibuka dengan kunci bernama “izin pengadilan”. Namun, realitas di lapangan menunjukkan banyaknya praktik “poligami gelap” atau nikah siri kedua/ketiga tanpa sepengetahuan istri pertama. KUHP Baru memandang ini sebagai bentuk penipuan status yang sangat mencederai martabat perempuan.
Pasal 402 ayat (2) menegaskan bahwa jika seseorang melangsungkan perkawinan dengan menyembunyikan status perkawinannya yang sah kepada pihak lain, ancaman pidananya adalah 6 tahun penjara. Ini adalah sanksi yang sangat berat, bahkan lebih tinggi dari ancaman hukuman beberapa tindak pidana kekerasan.
Secara akademis, hal ini disebut sebagai perlindungan terhadap informed consent dalam perkawinan; bahwa setiap orang berhak mengetahui status hukum calon pasangannya secara jujur. Informed consent dalam hal ini bermakna “Saya bersedia menikah denganmu karena saya tahu persis siapa kamu dan bagaimana status hukummu.” Jika status itu disembunyikan, maka hukum pidana hadir untuk melindungi hak korban yang telah dikelabui.
Nikah siri di Indonesia sering kali dipandang sebagai solusi jalan tengah. Namun, secara yuridis, nikah siri adalah “bom waktu”. Ketidakadaan pencatatan mengakibatkan tidak adanya perlindungan hukum. Berbagai kajian gender menyebutkan bahwa dampak terbesar dari nikah siri dirasakan oleh anak. Dalam KUHP Baru, praktik nikah siri yang berujung pada manipulasi dokumen kependudukan dapat terjerat Pasal 401 tentang Penggelapan Asal-usul.
Bayangkan skenario ini: sepasang suami-istri siri ingin membuat akta kelahiran anak. Karena tidak memiliki buku nikah, mereka “meminjam” nama orang lain atau memalsukan data agar anak mendapatkan akta. Tindakan ini secara tegas diancam pidana 6 tahun. Negara ingin memastikan bahwa identitas setiap anak adalah murni dan terlindungi, bukan hasil dari rekayasa administratif akibat pernikahan yang tidak diakui negara.
Bagi pasangan yang tetap bersikeras melakukan nikah siri meskipun tidak ada halangan hukum (sama-sama lajang), KUHP Baru menyiapkan Pasal 404. Pasal ini mengatur sanksi denda kategori II bagi mereka yang tidak melaporkan perkawinan, kelahiran, atau kematian kepada pejabat berwenang.
Mungkin bagi sebagian orang, hukuman denda terdengar ringan. Namun, secara akademis, ini adalah bentuk administrative penal law. Negara ingin menciptakan budaya hukum baru di mana setiap warga negara sadar bahwa mencatatkan perkawinan adalah kewajiban warga negara kepada negara, bukan sekadar pilihan sukarela.
Pertanyaan yang sering muncul di masyarakat adalah: apakah negara sedang mengkriminalisasi ajaran agama? Jawabannya adalah TIDAK. Negara tidak melarang rukun nikah dalam agama. Namun, negara menetapkan standar “legal standing”. Perkawinan yang sah secara agama memberikan ketenangan batin, namun perkawinan yang dicatatkan negara memberikan perlindungan lahir.
Pelanggaran atas batas ini terjadi ketika seseorang menggunakan dalih “sah agama” untuk menzalimi pihak lain misalnya, meninggalkan istri pertama tanpa nafkah melalui poligami siri, atau menghilangkan hak waris anak karena ketiadaan dokumen. Di sinilah KUHP Baru masuk sebagai “pedang” keadilan bagi pihak yang dirugikan.
Meskipun aturan ini tegas, masyarakat tidak perlu khawatir akan adanya “polisi moral” yang melakukan penggerebekan sembarangan. KUHP Baru tetap menghormati privasi keluarga melalui mekanisme delik aduan absolut. Artinya, proses hukum terkait perzinaan atau kohabitasi (jika pernikahan siri dianggap tidak sah) hanya bisa diproses jika ada pengaduan dari mereka yang terdampak langsung: suami/istri sah, orang tua, atau anak. Ini adalah keseimbangan yang cerdas antara penegakan hukum dan perlindungan ranah privat.
Melihat ancaman pidana yang tidak main-main dalam KUHP Baru, masyarakat perlu mengambil langkah preventif:
- Stop normalisasi nikah siri. Tokoh agama dan masyarakat harus mulai mengedukasi bahwa nikah siri adalah praktik yang merugikan perempuan dan anak secara hukum.
- Gunakan fasilitas isbat nikah. Bagi mereka yang sudah telanjur nikah siri, segera ajukan pengesahan (isbat) di Pengadilan Agama. Ini adalah satu-satunya jalan untuk memutihkan status hukum Anda dan menghindari jeratan Pasal 404 KUHP.
- Transparansi status. Sebelum menikah, mintalah bukti autentik status pasangan. Jangan hanya percaya pada ucapan lisan. Ingat, Pasal 402 ayat (2) melindungi Anda dari penipuan status.
Penegasan hukum dalam KUHP Baru melalui Pasal 401-405 adalah upaya berani untuk memodernisasi hukum keluarga kita. Negara ingin memastikan bahwa setiap ikatan suami istri melahirkan hak dan kewajiban yang nyata, bukan sekadar janji yang mudah diingkari karena ketiadaan bukti di atas kertas.
Marilah sama-sama dipahami bahwa kepatuhan pada hukum negara adalah bentuk ketaatan yang sejalan dengan nilai-nilai agama yang menjunjung tinggi keadilan dan perlindungan terhadap kaum lemah. “Sah di mata agama adalah fondasi spiritual, namun sah di mata negara adalah jaminan perlindungan yang legal”.