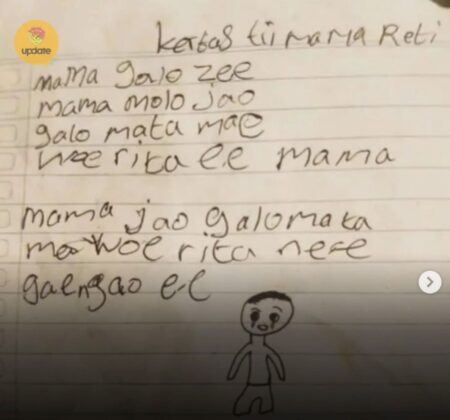Polemik Pernyataan Sekjen Kemenag dan Respons Akademisi
Polemik yang muncul dari pernyataan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama terkait guru madrasah memicu respons luas di kalangan publik. Isu ini menyentuh aspek sensitif yang berkaitan dengan martabat dan kesejahteraan para guru, sehingga menimbulkan berbagai reaksi, mulai dari kritik terbuka hingga kegelisahan kolektif.
Beberapa hari terakhir, ruang publik ramai membahas pernyataan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama yang disampaikan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VIII DPR RI. Dalam forum tersebut, Kamaruddin Amin menjelaskan masalah pengangkatan guru oleh yayasan yang sering kali dilakukan tanpa koordinasi dengan pemerintah. Ia menyampaikan bahwa banyak guru yang diangkat oleh yayasan tanpa sepengetahuan pihaknya, sehingga mengakibatkan tantangan dalam tata kelola dan alokasi dana.
“Kami diminta untuk membayarkan tunjangan profesinya pada tahun 2026,” ujarnya dalam rapat yang ditayangkan melalui kanal YouTube TVR Parlemen. Ia juga menyampaikan bahwa hingga saat itu, pihaknya belum memiliki data lengkap guru yang harus menerima tunjangan, sementara anggaran juga belum tersedia karena Kementerian Keuangan belum dapat mengalokasikan dana tanpa kejelasan data.
Pernyataan tersebut menyebut persoalan guru madrasah dan menuai beragam reaksi, mulai dari kritik terbuka, kegelisahan kolektif, hingga tanggapan yang diungkapkan oleh sebagian guru dan pemerhati pendidikan Islam.
Kepala Biro AUPK dan Kepegawaian sekaligus Pelaksana Tugas Kepala Biro A2KK dan Kemahasiswaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Drs. H. Ajam Mustajam, M.Si., menilai respons publik tersebut sebagai sesuatu yang wajar. Menurutnya, guru madrasah bukan sekadar profesi, melainkan simbol pengabdian panjang dalam sejarah pendidikan dan pembentukan karakter bangsa. Karena itu, setiap pernyataan pejabat negara yang menyentuh isu tersebut hampir pasti memunculkan perhatian luas.
“Respons publik tersebut patut dipahami sebagai ekspresi kepedulian, karena Guru madrasah bukan sekadar profesi, melainkan simbol pengabdian panjang dalam sejarah pendidikan dan pembentukan karakter bangsa,” kata Ajam, Rabu (4/2/2026).
Namun Ajam mengingatkan bahwa keadilan publik tidak hanya menuntut keberanian untuk mengkritik, tetapi juga kecermatan dalam membaca konteks. Ia menekankan bahwa dalam iklim demokrasi yang sehat, kritik merupakan bagian dari kontrol publik, tetapi keadilan narasi juga menuntut klarifikasi yang utuh, proporsional, dan tidak terjebak pada potongan kalimat yang terlepas dari konteks kebijakan.
Ajam Mustajam menilai, rapat dengar pendapat tersebut merupakan forum konstitusional yang memang dirancang untuk membahas tata kelola, keterbatasan struktural, dan tantangan kebijakan, termasuk dalam pengelolaan pendidikan keagamaan serta tenaga pendidiknya. Ia menegaskan bahwa bahasa yang digunakan dalam forum semacam itu lazim bersifat administratif dan teknokratis.
“Pernyataan Sekjen Kemenag sejatinya tidak dimaksudkan untuk merendahkan peran guru madrasah ataupun mengabaikan jasa historis dan sosiologis mereka. Yang disampaikan adalah realitas kebijakan negara, termasuk perbedaan sistem pengelolaan guru madrasah dibandingkan guru di bawah kementerian lain, terutama terkait formasi ASN, anggaran, skema kesejahteraan, dan realitas sistemik lainnya,” katanya.
Ia menilai persoalan muncul ketika bahasa birokrasi bertemu dengan akumulasi kekecewaan historis yang telah lama mengendap. Dalam situasi seperti itu, penjelasan teknis mudah dibaca sebagai penilaian normatif, meskipun maksud awalnya adalah menyampaikan argumentasi administratif.
Ajam menegaskan bahwa tidak ada keraguan sedikit pun mengenai posisi guru madrasah sebagai pilar pendidikan nilai, akhlak, dan moderasi beragama. Menurutnya, para guru madrasah hadir hingga ke pelosok negeri, sering kali dalam keterbatasan sarana, fasilitas, dan kesejahteraan. Dalam sejarah Indonesia, madrasah dan para gurunya bahkan telah berperan strategis jauh sebelum sistem pendidikan nasional tertata secara formal.
Dalam analisisnya, Ajam menyebut setidaknya ada tiga faktor yang memicu kesalahpahaman. Pertama, adanya narasi yang terpotong dari keseluruhan konteks dialog kebijakan. Kedua, jarak antara bahasa administratif birokrasi dan bahasa empati publik. Ketiga, persoalan struktural serta akumulasi kekecewaan lama terkait status, kesejahteraan, dan kepastian karier guru madrasah.
Ajam Mustajam menilai klarifikasi tersebut seharusnya dipahami sebagai bagian dari upaya meluruskan makna, bukan sekadar pembelaan diri. Ia menekankan bahwa guru madrasah tidak membutuhkan pengakuan simbolik semata, melainkan kebijakan nyata yang konsisten dan berjangka panjang.
Menurutnya, polemik ini justru dapat menjadi momentum refleksi bersama bagi negara, DPR, dan publik. Ia mendorong agar suara guru madrasah dijadikan dasar untuk menyusun kebijakan kesejahteraan yang lebih adil, memperjuangkan anggaran berkelanjutan, menata ulang status dan pengembangan karier, serta membangun komunikasi kebijakan yang lebih empatik tanpa kehilangan akurasi administratif.
Ajam juga mengingatkan bahwa kehati-hatian dalam memilih diksi tidak boleh mematikan keberanian untuk menyampaikan fakta. Etika komunikasi publik, menurutnya, bukan hanya soal bahasa yang halus, tetapi juga kejujuran agar persoalan dapat diselesaikan bersama. Di sisi lain, publik pun diharapkan memberi ruang bagi pejabat untuk menjelaskan keterbatasan sistemik secara jujur tanpa serta-merta menariknya sebagai stigma moral.
Ia menekankan bahwa polemik seharusnya tidak berhenti pada perdebatan, melainkan bergerak menuju pembenahan sistemik. Klarifikasi, baginya, adalah jalan untuk menjaga agar diskursus publik tetap sehat, jujur pada realitas, adil pada profesi, dan setia pada tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan nilai dan etika.